Silahkan Mencari!!!
I'M COMEBACK...SIBUK CUY...KERJAAN DI KANTOR GI BANYAK BANGET...JD G BISA POSTING DEH...
AKHIRX OTAK Q PRODUKTIF LAGI BUAT FF BARU...
GOMAWOYO BWT YG DAH MAMPIR & COMMENT
HWAITING!!!
AKHIRX OTAK Q PRODUKTIF LAGI BUAT FF BARU...
GOMAWOYO BWT YG DAH MAMPIR & COMMENT
HWAITING!!!
Sabtu, 07 Mei 2011
Silent Road (Chapter 7)
Chapter 7
Sebuah Keputusan
Kalimatnya indah. Tatap matanya menggetarkan hati. Bahkan, Kim Bum pun tak pernah memandangnya begitu tajam, tak pernah mengucapkan kata-kata seindah itu....
* * *
”Saya akan pulang, Nek,” kata Kim So Eun.
“Sepagi ini? Ada masalah, Kim So Eun?” Nenek Seo Woo Rim menyentuh bahunya.
“Saya tak bisa menjelaskan. Tapi, saya harus pergi secepatnya.”
“Kalau itu yang terbaik, lakukanlah,” kata Nenek Seo Woo Rim.
“Terima kasih. Akan ada seseorang yang datang mencari saya. Tolong, berikan lukisan ini padanya. Dia akan mengerti,” kata Kim So Eun, sambil mengulurkan lukisannya.
Nenek Seo Woo Rim mengangguk tanpa suara.
Kim So Eun menggigit bibir. Lukisan senja dalam tatapannya perlahan mengabur. Dia ingat senja itu. Senja saga di tebing Earth Land.
* * *
Kim So Eun sedang melukis di beranda belakang ketika bel pintu berbunyi. Ia mengamati hasil karyanya. Lukisan setengah jadi. Lukisan hitam-putih dengan medium pensil. Teknik melukis yang sudah lama tidak ia gunakan. Ia menghela napas panjang, lalu menutup lukisan itu dengan selendang.
“Sedang sibuk?” Kim Bum menyapanya di ambang pintu.
Kim So Eun menggeleng, sambil tersenyum.
“Gerai perhiasan menelepon, cincin kita sudah siap. Kita ambil sekarang? Kita kan harus mencoba cincin itu. Mungkin saja tidak pas.”
Cincin itu sudah telanjur jadi. Sekalipun tidak nyaman di jari, tindakan apa yang bisa dilakukan untuk mengubahnya?
Kim Bum mengamati perangkat lukis yang bertebaran. “Kau sedang melukis rupanya. Kalau begitu, kita ambil cincin itu lain hari. Mood seniman tidak selalu datang setiap saat, bukan? Melukis apa?”
Kim So Eun terdiam. Ia tak ingin menjawab pertanyaan itu. Ia ingin menyembunyikan sesuatu. Entah apa. Sebelum menjawab, Kim Bum telah menarik selendang penyelubung lukisan. Lukisan setengah jadi itu tampak jelas. Lukisan tentang bayangan seorang laki-laki tanpa wajah. Tampak postur dari belakang, memperlihatkan punggung dengan rambut pendek agak keriting dan acak-acakan sedang melangkah menjauh.
Kim Bum menatap lukisan itu. “Kau memakai pensil. Sudah lama kau tidak melukis dengan pensil. Siapa dia?”
Kim So Eun terkejut. “Bukan siapa-siapa. Waktu di Earth Land, aku sering duduk di beranda. Banyak pejalan kaki melintas di depan rumah Nenek Seo Woo Rim. Bagiku, mereka fenomena menarik. Karena aku tidak mengenal mereka, aku tidak menampakkan wajah mereka. Sebab, menggambar wajah memerlukan pendalaman karakter. Jadi, kupilih menggambar punggung mereka.”
“Sudut pandang yang menarik. Tapi, kalau boleh kukatakan, karakter punggung ini terlalu bergaya ‘kota’. Dia mengenakan T-shirt dan jins. Seragam anak muda perkotaan.”
“Earth Land bukan pedalaman. Ada angkutan kereta api yang memungkinkan alur kehidupan kota memengaruhi gaya hidup mereka. Ayo, kita pergi,” kata Kim So Eun, mengalihkan pembicaraan.
“Nanti pulangnya diantar sopir, ya. Sore nanti aku harus presentasi,” kata Kim Bum, sambil membuka pintu mobil.
Kim So Eun tertegun. Kim Bum membiarkan dia pulang sendiri. Padahal, di suatu tempat, seseorang begitu peduli padanya, bahkan bersedia berjalan di belakangnya, untuk mengantarnya melewati hutan.
Kim So Eun mematut diri di depan cermin. Berbalut gaun putih selutut, rambut ditata rapi dengan sematan bunga putih. Pantulan wajahnya begitu cantik. Serupa peri bunga di buku dongeng.
“Sudah siap? Fotografer sudah menunggu,” kata Kim Bum.
Kim So Eun beranjak. Sekilas ditatapnya cermin untuk melihat bayang dirinya. Ia terkejut saat menyadari bahwa di dalam cermin bayangan dirinya tidak sendirian lagi. Kim Bum mendampinginya. Seorang pria gagah berjas kasual. Wajahnya bersih menyimpan senyum. Matanya menyorot tajam, menyiratkan ketakjuban. Mereka bertemu pandang lewat pantulan cermin.
“Akan kulakukan apa pun untukmu. Tidak akan pernah kau temukan cinta lain seindah yang aku miliki untukmu,” kata Kim Bum.
Kim So Eun memejamkan mata. Benarkah tidak ada cinta seindah cinta Kim Bum padanya? Lalu, bagaimana dengan cinta Jung Il Woo? Dua cinta yang indah. Manakah yang lebih indah?
Ketika pemotretan, Kim So Eun tampak selalu gugup dan salah tingkah sehingga berkali-kali ia ditegur oleh sang pengarah gaya.
“Apakah kau baik-baik saja?” tanya Kim Bum, seusai sesi foto.
Kim So Eun mengeluh, “Aku tidak pernah merasa nyaman difoto.”
“Kau tampak gelisah, seperti memikirkan sesuatu,“ kata Kim Bum, sambil menggenggam jemari Kim So Eun. “Tak usah terlalu memikirkan hari pernikahan kita. Kau hanya perlu mempersiapkan dirimu sebaik mungkin untuk menjadi pengantinku yang tercantik.“
Kim So Eun tercenung. Itu impian Kim Bum. Sanggupkah diwujudkannya mimpi itu untuk Kim Bum? Sementara, dirinya kini adalah diri yang terbelah, yang menyimpan bayang pria lain di sudut hati.
Kim Bum dan Kim So Eun bersama mengamati foto-foto pranikah mereka. Sebagian besar foto hitam-putih, merefleksikan diri mereka dalam berbagai gaya. Ada yang tampak romantis, ada yang tidak.
Kim So Eun tertegun. Seolah ia terlempar pada suatu waktu. Pada sebuah malam, pada sebuah beranda. Ketika sebuah bayang merangkumnya dalam pelukan dan memberinya sebuah kecupan menggetarkan. Getaran yang masih tersisa hingga hari ini. Jantung Kim So Eun berdegup keras, hingga mengucurkan keringat dingin di tengkuknya.
“Kau pucat sekali. Ada apa?“ seru Kim Bum.
Kim So Eun mengatur napas, lalu mengerjapkan mata. Di depannya sepasang mata tampak menyimpan kecemasan. Cemas yang berasal dari cinta yang begitu besar. Cinta Kim Bum untuknya. Tapi, apa yang dilakukannya untuk membalas cinta itu?
Kim So Eun menghindar dari tatapan itu, tanpa mampu menyembunyikan gelisah. “Kita pergi saja,” katanya, sambil beranjak.
Kim Bum menghentikan gerak gadis itu. Matanya menatap tajam penuh selidik. “Ada apa?” tanyanya, lebih tegas.
Kim So Eun terdiam. Dia benar-benar tersudut, tiada celah untuk berkelit.
“Aku tidak siap,” katanya, pelan.
“Apa maksudmu? Kau tidak siap menikah denganku?” tanya Kim Bum.
Anggukan pelan Kim So Eun membuat Kim Bum terkesiap.
“Apa artinya? Kita sudah sejauh ini dan kau bilang tidak siap? Apa yang sebenarnya terjadi?” Suara Kim Bum gemetar.
Bibir Kim So Eun bergetar. Bagaimana menjelaskan apa yang terjadi bila dirinya sendiri juga tidak paham akan apa yang ada dalam benaknya?
Hening. Waktu berlalu dalam diam. Entah berapa lama. Sesaat kemudian terdengar helaan napas panjang. Napas Kim Bum.
“Aku merasa, kau sedang memikirkan orang lain. Apakah ia pemilik punggung dalam lukisanmu?” gumam Kim Bum, dingin.
Sunyi. Tidak ada suara dan gerak apa pun juga. Hampa. Kim So Eun tahu, inilah akhirnya. Dia telah sampai pada suatu jalan. Jalan buntu.
Ditutupnya wajah dengan seluruh jemarinya. Bukan untuk menahan air mata, tapi untuk menyembunyikan diri. Tak mampu dia berdiri di hadapan Kim Bum, apalagi bersanding di pelaminan. Adakah yang lebih hina daripada yang dilakukannya saat ini? Adakah yang lebih memalukan daripada apa yang terjadi padanya saat ini? Dia, seorang calon pengantin, menyimpan bayang lelaki lain dalam benaknya.
“Maaf...,” gumam Kim So Eun.
Kim Bum menggigit bibir, gigitan keras yang menimbulkan luka. Pedih, tapi tak sebanding dengan kepedihan di hati.
“Jangan katakan apa pun. Kita sama-sama sedang emosi. Yang perlu kita lakukan saat ini adalah pulang. Lalu, kita akan bertemu lagi, sesudah kau dan aku siap untuk itu,” kata Kim Bum. Kalimat itu begitu dingin, lurus, datar, dan tak terbantah.
Suatu pagi Kim Bum datang. Bibirnya tersenyum. Matanya tidak.
“Kau marah padaku?” tanya Kim So Eun, ragu.
Kim Bum terdiam sesaat, lalu menggeleng.
“Benci?” tanya Kim So Eun lagi.
“Tidak. Hanya, aku merasa tidak mengenalmu. Kebersamaan kita yang sekian lama itu ternyata tidak berarti.”
Kim So Eun menunduk. Rasa bersalah menyudutkannya.
Kim Bum menyentuh bahunya. Tatap matanya lembut “Seharusnya, aku yang shock. Tapi, mengapa sepertinya kau yang lebih tertekan?”
Kelembutan Kim Bum sesungguhnya sangat menyentuh hati. Tapi, bagi Kim So Eun, kelembutan itu justru lebih tajam dari pisau mana pun juga. Andai boleh memilih, Kim So Eun lebih siap menerima kemarahan.
“Aku bersalah padamu,” bisik Kim So Eun, bergetar.
Kim Bum menghela napas panjang. “Beberapa hari ini aku merenung. Bukan hal mudah menentukan sebuah keputusan. Tapi, ini tak bisa dihindari. Apa pun alasannya, kita harus bersama menghadapinya. Merenung membuatku menemukan satu hal, yaitu bahwa cinta seharusnya bukanlah sesuatu yang egois. Kebahagiaan terbesar dalam proses mencintai seseorang adalah membuatnya bahagia. Begitu juga aku. Aku sangat mencintaimu. Tapi, aku bukan manusia yang sempurna sehingga cinta yang kupunya tak cukup membahagiakanmu.”
“Kim Bum, bukan itu....”
“Karena itu, aku tidak akan membuat diriku menjadi duri dalam daging bagi hidupmu. Malapetaka terbesarku adalah jika cintaku mengikatmu dan membuatmu kehilangan kesempatan untuk meraih kebahagiaanmu. Dia, si pemilik punggung itu, barangkali mempunyai sesuatu yang tak kupunya. Sesuatu yang membuat hatimu terbelah. Jangan mengingkari hatimu sendiri. Yang penting, temukan kebahagiaanmu. Selama itu akan membahagiakanmu, aku rela melepasmu.”
Kim So Eun terpana, sungguh tak terduga. “Jadi?”
“Terserah padamu. Aku tak punya hak mengendalikan hidupmu. Kita masing-masing berhak atas hidup kita sendiri. Aku bisa memaksamu melakukan itu. Tapi, apakah itu layak kulakukan? Apakah bisa hatimu kurebut dengan paksaan? Tidak, aku tidak akan pernah melakukan itu. Aku akan mendapat cintamu bila memang hatimu menginginkan itu. Bukan karena alasan lain. Jadi, jangan menipuku atau dirimu sendiri.”
Kim So Eun menatap mata Kim Bum. Tampak bening, tapi tidak bercahaya. Mata itu menyimpan kepedihan, memohon kejujuran. Permohonan yang harus dihargai, meski berarti menambah kepedihan.
Kim So Eun menghentikan langkah. Pondok kayu di bantaran sungai itu masih sama seperti saat ditinggalkannya beberapa bulan lalu.
Bersambung…
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
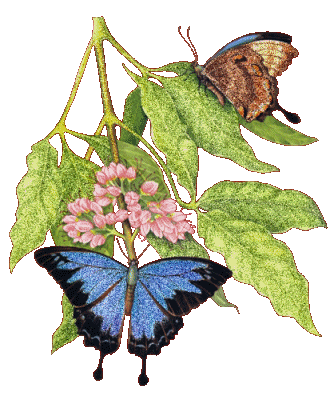
Tidak ada komentar:
Posting Komentar