Silahkan Mencari!!!
I'M COMEBACK...SIBUK CUY...KERJAAN DI KANTOR GI BANYAK BANGET...JD G BISA POSTING DEH...
AKHIRX OTAK Q PRODUKTIF LAGI BUAT FF BARU...
GOMAWOYO BWT YG DAH MAMPIR & COMMENT
HWAITING!!!
AKHIRX OTAK Q PRODUKTIF LAGI BUAT FF BARU...
GOMAWOYO BWT YG DAH MAMPIR & COMMENT
HWAITING!!!
Sabtu, 07 Mei 2011
Silent Road (Chapter 2)
Chapter 2
Sindrom Pra-nikah
Kim Bum tersenyum “Hari bahagia, tentunya. Aku suamimu dan kau istriku. Kita hidup bersama dan saling memiliki secara utuh. Kita bisa saling memeluk sepanjang hari.”
Pipi Kim So Eun kembali merona “Apakah itu berarti kita harus selalu berdua ke mana pun kita pergi?”
“Paling tidak, begitulah.”
“Lalu, bagaimana dengan teman-temanku? Selama ini aku mengalami banyak hal yang menyenangkan bersama mereka. Cerita ini-itu, belanja, mencari restoran baru….”
“Tentu kau tetap akan bisa menikmati hal-hal itu bersama mereka. Pernikahan bukan berarti membuat hidup kita terisolasi dari orang lain. Kahlil Gibran mengatakan: “Bernyanyi dan menarilah bersama dalam segala sukacita. Hanya, biarkanlah masing-masing menghayati ketunggalannya.”
Kim Bum meneguk es teh tawar, lalu melanjutkan, “Jadi, meskipun hidup bersama, kita harus tetap memiliki waktu untuk diri sendiri. Kita masing-masing tetap melakukan kegiatan favorit, sesuai pilihan masing-masing. Aku akan tetap bermain basket dan memancing, sementara kau melukis dan berkumpul dengan teman-temanmu, tanpa harus kudampingi. Hanya, waktu dan porsinya saja yang perlu disesuaikan.”
“Misalnya?”
“Clubbing jangan sampai lewat tengah malam dan jangan terlalu sering. Akhir pekan khusus untuk kita berdua.”
“Tiga kali seminggu clubbing, bagaimana?”
“Bagaimana kalau satu kali?” Kim Bum menawar.
“Cuma satu kali? Kita ambil jalan tengah saja. Dua bagaimana?“ Kim So Eun juga menawar.
Kim Bum mengangguk. “Awal yang baik. Kita telah belajar untuk menyelesaikan masalah dengan kompromi. Untuk selanjutnya, kompromi semacam ini harus banyak kita lakukan, ditambah dengan kejujuran dan toleransi.“
Kim So Eun menghela napas. Kekawatiran mendadak menerpanya. Baru ia sadari bahwa apa yang dikatakannya memang benar. Ia memang telah mempersiapkan segala macam. Tapi, semua itu hanya bersifat fisik. Ia justru melupakan apa yang ada di dalam dirinya.
“Apakah aku siap?” bisiknya, ragu.
“Maksudmu?” Kim Bum meneliti tingkah Kim So Eun. Ia baru tersadar bahwa Kim So Eun tampak gelisah.
“Menjadi seorang istri…,” sambung Kim So Eun, bergumam.
“Tentu siap, mengapa tidak?”
Kim So Eun menghela napas, berkata hati-hati, “Aku khawatir, apakah mampu menjalani peran itu. Hidupku pasti akan sangat berubah. Aku bukan lagi seorang yang bebas. Artinya, aku bukan lagi menjadi seseorang yang berdiri sendiri, melainkan seorang istri yang mendampingi suami. Karena itu, apa yang ada padaku harus kubagi denganmu. Kebahagiaan dan juga kesedihan. Dan, setiap kali akan melakukan sesuatu, aku harus memperhitungkan keberadaanmu. Aku tak bisa lagi hanya mementingkan egoku.”
“Kau merasa kesulitan melakukan itu?” kata Kim Bum, sambil menatap tepat di manik mata Kim So Eun.
“Aku….” Kim So Eun ragu-ragu.
Kim Bum meraih jemari Kim So Eun. Dengan lembut ia menggenggam jemari itu, seolah menyalurkan ketenangan.
“Memang benar. Hidup kita akan mengalami perubahan besar. Tapi, kau kan tidak akan sendirian menghadapinya. Aku akan selalu bersamamu menghadapi ini semua.”
“Kita akan saling belajar menjalani perubahan itu. Dan, karena kita adalah dua pribadi yang berbeda, jadi yang kita perlukan adalah toleransi. Dalam proses belajar ini akan terjadi banyak kealpaan. Ada banyak kebiasaan dalam diri kita yang mungkin kita lakukan begitu saja, yang mungkin tidak sesuai dengan pasangan kita. Di sinilah toleransi diperlukan. Kita harus selalu sadar bahwa ada faktor alpa sehingga kita perlu saling mengingatkan, bukannya terbawa alpa dan emosi masing-masing.”
“Kau tahu, aku punya banyak kebiasaan buruk,” sela Kim So Eun mulai tenang, “tidak bisa bangun pagi, tidak bisa memasak….”
“Takut gelap, malas sikat gigi,” sambung Kim Bum.
“Ssst, sudah, nanti orang lain tahu,“ Kim So Eun mencubit lengan Kim Bum.
“Biar saja,“ Kim Bum tertawa. “Biar dunia tahu, betapa baik hatinya aku, sudi mencintai seorang gadis cantik yang malas sikat gigi.”
Kim So Eun manyun dan menyimpan tawanya.
“Mungkin, kau mengalami depresi,” kata Kim Bum dalam perjalanan pulang. “Kesibukan mempersiapkan segala sesuatu untuk pernikahan kita, mungkin memunculkan banyak tekanan dalam dirimu.”
“Mungkin. Entahlah,” kata Kim So Eun, sambil angkat bahu.
“Barangkali, ada baiknya kau beristirahat. Lupakan dulu semua persiapan ini. Biar kuambil alih saja. Atau, bisa juga kita istirahat sejenak. Toh, waktunya relatif panjang,” Kim Bum mengajukan usul.
“Jangan, persiapan sudah hampir tuntas! Aku akan baik-baik saja. Barangkali, aku hanya kelelahan atau stres.”
“Kim So Eun, stres yang berkepanjangan bisa berbahaya.”
“Kau keberatan memiliki calon istri yang agak sinting?”
“Sangat.”
“Baiklah, aku akan spa seharian penuh. Dipijat, mandi bunga, makan enak. Kalau perlu, plus melamun. Sesudah itu, aku jamin, aku tidak akan stres lagi. Bagaimana?”
“Kau yakin cukup dengan itu?”
Sambil tersenyum, Kim So Eun mengangguk pasti.
Musik mengalun merdu. Entah apa lagunya. Barangkali, judul tidak terlalu penting. Yang jelas, denting piano dipadu dengan petikan gitar dan alunan alat musik lain yang berpadu serasi. Menciptakan keindahan yang membelai hati, mengalirkan rasa damai yang nyaman.
Kim So Eun menghirup napas. Wangi bunga memenuhi rongga paru-paru, mengalirkan kesegaran pada seluruh ruang tubuh. Begitu segar oksigen wangi itu membuat tubuhnya ringan seperti melayang.
Apalagi, ditambah dengan pijatan di seluruh bagian tubuh, termasuk bahu, leher, punggung, kaki, dan lengan. Mengendurkan segala otot yang meregang, melenturkan segala persendian. Yang muncul kemudian adalah rasa nyaman luar biasa. Lalu, berendam di dalam air hangat bertabur bunga adalah penuntasan yang sempurna.
Kim So Eun menikmati setiap tahap ritual spa dengan sepenuh hati. Dia berharap, proses itu akan membantu melarutkan segala beban hati dan kepenatan tubuh. Berharap bahwa ia akan mendapatkan energi baru untuk melanjutkan persiapannya menuju hari barunya sebagai mempelai untuk Kim Bum.
“Lihat, aku telah bugar kembali,” seru Kim So Eun, antusias, ketika Jung So Min, sahabatnya, menjemput di ambang pintu. “Sekarang, ayo, kita makan enak. Lupakan diet, abaikan berat badan.”
“Kurasa, ini tidak cukup untukmu,” Jung So Min menatapnya.
“Maksudmu?”
“Program spa ini hanya efektif menyegarkan tubuhmu. Kalau saat ini kau merasa beban hatimu menghilang, itu karena efek kebugaran tubuhmu yang bersifat sementara, paling-paling hanya akan bertahan dalam hitungan hari.”
“Lalu, sesudah itu, aku akan gelisah lagi? Begitu maksudmu?”
Jung So Min mengangguk.
“Mengapa kau berpikir begitu?” tanya Kim So Eun mendesak.
“Kuduga, kau mengalami semacam sindrom. Barangkali, ini mirip sindrom Baby Blues yang dialami wanita pasca melahirkan. Padamu adalah sindrom pra-nikah. Kau gelisah karena memikirkan pernikahanmu, memunculkan berbagai pikiran negatif, dan akhirnya membuatmu merasa tidak siap.”
“Persis seperti itu. Aku jadi was-was dan ketakutan akan apa yang terjadi nanti. Aku mendadak khawatir hidupku akan terkekang, lalu kehilangan teman. Aku bahkan meragukan kemampuanku untuk menjadi istri yang baik bagi Kim Bum.”
“Ketakutan yang tidak semestinya.”
“Itulah. Aku juga bingung mengapa begitu?”
Jung So Min menghela napas. “Kasus semacam ini sepantasnya hanya terjadi pada pasangan yang dijodohkan sehingga mereka belum sempat mengenali karakter masing-masing. Atau, strata sosial yang berbeda akan membuat gaya hidup mereka tidak seimbang.”
Kim So Eun tercenung. Ya, sesungguhnya memang tidak layak kalau dia mengalami sindrom ini. Kim Bum adalah pilihannya sendiri. Mereka sudah bertahun-tahun menjalin hubungan. Rentang waktu itu membuktikan bahwa Kim Bum adalah pilihan terbaik untuknya. Jadi, mengapa harus muncul segala kegelisahan ini?
“Aku…,” kalimat Kim So Eun tersendat, tertekan rasa putus asa.
“Itulah yang namanya sindrom. Datang seperti virus, tanpa bisa dicegah. Tapi, jangan khawatir. Ayo, kita cari solusinya bersama-sama,” kata Jung So Min, berusaha menenangkan.
“Apa yang harus kulakukan?” tanya Kim So Eun, pasrah.
Jung So Min berpikir sesaat.
“Rasanya, kau perlu refreshing beberapa hari. Liburkan dirimu dari rutinitas, kosongkan pikiran, dan lupakan segala urusan. Kau bisa pergi ke suatu tempat yang belum pernah kau kunjungi dan lakukan apa pun yang kau sukai,” kata Jung So Min, memberi saran.
Kim So Eun tampak bingung. Tak yakin pada pilihan yang diberikan Jung So Min.
“Coba saja. Paling tidak satu minggu. Lakukan dengan maksimal. Bebaskan hatimu dari segala beban. Bila mungkin, lupakan kami semua untuk sementara. Putuskan kontak, termasuk dengan Kim Bum.”
“Kau yakin itu semua akan berhasil?”
“Abaikan berbagai kemungkinan tentang hasilnya. Itu juga termasuk beban yang bisa mengganggu. Yang penting, bebaskan hati, jalani hari seperti air mengalir….”
“Masalahnya, aku harus pergi ke mana?”
“Pilih sesuka hatimu. New Caledonia, Barcelona, atau Macau? Semua terserah kau.”
Kim So Eun menggeleng. “Aku tidak mau tinggal di hotel sendirian. Tapi, tempat wisata yang terlalu ramai juga akan mengganggu.”
“Jadi, tempat macam apa yang kau inginkan?”
Kim So Eun mengerjapkan mata. “Suatu tempat yang sunyi. Ada banyak pohon hijau, seperti desa atau hutan. Aku akan melukis di antara keteduhan pohon-pohon itu.”
“Ha, aku tahu!” seru Jung So Min, seolah baru menemukan sesuatu. “Kau ke desa nenekku saja.”
“Di mana?” Kim So Eun antusias.
“Earth Land. Sebuah desa kecil yang penuh hutan karet, ladang cokelat, dan sungai di lembah. Tempat yang sangat inspiratif untukmu.”
Mata Kim So Eun membesar, menyiratkan imajinasi yang berkelana.
“Kalau begitu, antar aku ke sana.”
“Tidak! Sudah kukatakan, proses ini akan memberikan hal baru untukmu. Karenanya, jangan melibatkan lingkungan lama dalam proses ini. Petualangan sudah akan dimulai sejak menit pertama keberangkatanmu.”
“Tapi, nenekmu kan tidak mengenalku.”
“Sudah. Aku sering bercerita tentang teman-temanku padanya. Jadi, kau tak perlu khawatir. Nanti akan kukirim kabar padanya.”
“Lalu, bagaimana caranya aku pergi ke sana?”
“Gampang, naik pesawat saja sampai di ibu kota provinsi, lalu disambung dengan kereta api. Turunlah di stasiun Earth Land. Dari stasiun ada Kereta Kuda yang bisa mengantarmu sampai di rumah Nenek. Asyik, ‘kan?”
Skema perjalanan yang sangat menjanjikan. Menggambarkan petualangan baru yang unik. Tak bisa tidak, Kim So Eun merasa harus segera berangkat. Bisa jadi, ini akan menjadi petualangan menarik di hari-hari akhirnya sebagai wanita lajang. Sebelum dia berubah status menjadi Nyonya Kim Bum!
Bersambung…
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
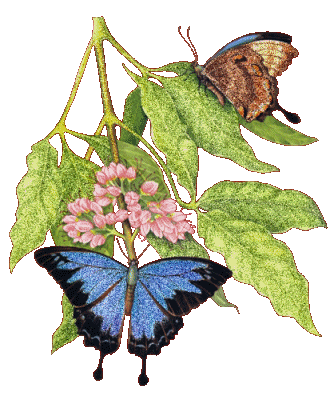
Tidak ada komentar:
Posting Komentar