Silahkan Mencari!!!
I'M COMEBACK...SIBUK CUY...KERJAAN DI KANTOR GI BANYAK BANGET...JD G BISA POSTING DEH...
AKHIRX OTAK Q PRODUKTIF LAGI BUAT FF BARU...
GOMAWOYO BWT YG DAH MAMPIR & COMMENT
HWAITING!!!
AKHIRX OTAK Q PRODUKTIF LAGI BUAT FF BARU...
GOMAWOYO BWT YG DAH MAMPIR & COMMENT
HWAITING!!!
Sabtu, 07 Mei 2011
Silent Road (Chapter 5)
Chapter 5
Lelaki Senja
Suatu petang Jung Il Woo membuktikan janjinya. Dia menemukan Kim So Eun di antara jajaran pohon karet. Siang itu agak panas sehingga Kim So Eun bermaksud menikmati keteduhan di sana. Dibawanya perangkat lukis, berharap akan menemukan objek yang menarik. Tapi, bukannya ide yang datang, justru kantuk yang membuai. Kim So Eun bersandar pada sebatang pohon dan tertidur.
Beberapa saat kemudian helaian kelopak bunga jatuh menyentuh pipinya. Kim So Eun membuka mata. Astaga, Jung Il Woo sedang berjongkok di sampingnya.
“Kau mengagetkanku. Sedang apa di sini?”
Jung Il Woo tersenyum. “Menunggumu bangun.”
“Anginnya sangat nyaman. Mengapa kau membangunkanku?”
“Harus. Sebentar lagi gelap. Apalagi di hutan seperti ini. Gelap lebih cepat datang, juga binatang malam.”
Refleks Kim So Eun melompat dan berdiri.
“Tidak perlu tergesa, ini masih petang, masih ada waktu. Jadi, kau pelukis? Tapi, kanvasmu masih kosong. Belum menemukan ide?” tanya Jung Il Woo, sambil menunjuk alat-alat lukisnya.
Kim So Eun menggeleng. Jung Il Woo meraih tangannya dan membawa gadis itu mengikuti langkahnya. “Kutunjukkan sesuatu yang inspiratif.”
Jung Il Woo membawa Kim So Eun pada sebuah tempat di ketinggian. Di bawahnya terhampar sebuah lembah. Lembah di kaki gunung dengan alur sungai berkelok-kelok, berair bening, membelah hutan pinus dan hutan karet pada kedua sisinya.
“Lembah yang cantik,” gumam Kim So Eun, takjub.
“Tunggulah, sebentar lagi efek matahari tenggelam akan memunculkan kesan magis yang unik.”
Benar. Sesaat kemudian, ketika matahari mulai bersembunyi di balik bukit, sisa sinarnya memunculkan semburat cahaya jingga. Dari tempatnya berdiri, Kim So Eun melihat jelas pergerakan cahaya melewati daun-daun. Hutan bagai berlapis warna, ada semburat cahaya kuning, jingga, dan merah saga.
“Luar biasa. Indah sekali,” Kim So Eun kehilangan kata-kata.
“Rekam dalam benakmu. Perhatikan sedetail mungkin dan besok pindahkan ke kanvasmu,” bisik Jung Il Woo.
Saran yang baik.
“Menakjubkan, bukan? Aku melihatnya hampir setiap hari. Itu salah satu yang membuatku betah di sini,” kata Jung Il Woo.
“Salah satu? Berarti ada yang lain?”
“Tentu saja. Ada hutan karet yang menidurkanmu tadi, aliran sungai, dan bulan purnama di tebing ini. Kalau beruntung, seusai hujan terkadang muncul pelangi di sini.”
“Sungguh? Aku sudah lama tidak melihat pelangi.”
“Kalau begitu, berdoalah minta hujan di siang hari. Siapa tahun Tuhan bermurah hati memunculkan pelangi untukmu. Sekarang, ayo, kuantar pulang.” Jung Il Woo mengulurkan tangan.
“Kau pasti ingin tahu di mana aku tinggal,” kata Kim So Eun.
“Aku sudah tahu. Rumah Nenek Seo Woo Rim, ‘kan?”
Kim So Eun mengerling. “Lalu, untuk apa mengantarku? Malam baru mulai. Aku bisa pulang sendiri.”
“Di kota, malam seperti ini memang masih dini. Di sini pun kondisi sosial relatif aman. Tapi, ingat, ini hutan karet. Kau tak berbekal cahaya. Ada beberapa binatang malam yang terkadang muncul begitu saja. Meski tidak menyerang, akan cukup mengagetkan dan pasti membuatmu panik. Aku tidak yakin kau mampu mengatasinya sendirian.”
Kim So Eun terenyak. Ia baru ingat harus melewati hutan karet.
“Oke, kalau kau keberatan, begini saja, aku akan berjalan beberapa meter di belakangmu. Sampai di batas perkampungan, kau bisa pulang sendiri. Bagaimana?”
Kim So Eun menunduk. “Lebih baik kita berjalan bersama-sama saja.”
Jung Il Woo mengangkat alis, matanya tertawa menggoda. “Yakin?”
Pipi Kim So Eun merona dadu. Dianggukkannya kepala, mencoba menyembunyikan rona wajahnya. Tapi, Jung Il Woo telanjur melihatnya. Cahaya bulan membantu pria itu melihat ranum dadu di pipi Kim So Eun.
Siang sudah terik ketika Kim So Eun menyudahi lukisannya. Lukisan tentang senja eksotis di lembah yang dilihatnya kemarin. Lukisan itu belum selesai, masih memerlukan penyempurnaan. Kim So Eun tidak membawa semua perlengkapan lukisnya. Tapi, sebagai sketsa awal, cukuplah. Kim So Eun ingin menunjukkannya pada Jung Il Woo.
Ragu-ragu Kim So Eun menghentikan langkah. Pondok kayu yang dicarinya ada di bantaran sungai. Pondok itu sederhana, hanya berhias pintu dan jendela tanpa tirai yang terbuka lebar. Diketuknya pintu.
Suara Jung Il Woo menjawab ketukan. Setengah menit kemudian Jung Il Woo muncul di ambang pintu dan mengajaknya masuk.
Kim So Eun ragu-ragu. Nalurinya mengatakan, Jung Il Woo sedang melakukan sesuatu. Gerakannya tampak terburu-buru. Anehnya, ada semacam tepung putih pada hidung dan lengannya.
“Sedang sibuk?” tanya Kim So Eun.
“Tidak, masuklah.” Jung Il Woo membuka pintu lebih lebar.
“Tapi, ada tepung menempel,” Kim So Eun memberikan isyarat.
Jung Il Woo mengusap hidung dengan lengannya.
“Kau sedang melakukan sesuatu. Lebih baik tidak kuganggu. Lain kali aku datang lagi.” Kim So Eun beranjak pergi.
“Tunggu, aku sama sekali tidak terganggu. Aku sedang memasak.”
Mata Kim So Eun membesar. Jung Il Woo mengajak Kim So Eun mengikuti langkahnya.
“Masak apa?” tanya Kim So Eun, heran.
“Tumis sawi dan bakwan kampung.”
“Kau pandai memasak?”
“Apa susahnya? Tumis sawi cuma memerlukan bawang putih dan garam. Untuk bakwan, campur saja semua bahan: terigu, telur, wortel, taoge, beri air sedikit, dan digoreng kecil-kecil. Sangat gampang.”
Kim So Eun takjub. Jung Il Woo menjelaskan semua itu dengan lancar. Gerakan tangannya saat memotong sayuran dan mengaduk adonan juga sangat luwes. Sungguh tidak terduga. Sama sekali tidak terlintas di benaknya bahwa teman barunya ini mampu menguasai dapur dengan sangat baik.
“Belajar dari mana?” Kim So Eun tak mampu menahan rasa ingin tahu.
“Ibuku. Ayah meninggal sejak aku balita. Jadi, kami banyak melakukan hal bersama, termasuk memasak.”
“Tapi, kau tetap maskulin.”
Jung Il Woo tergelak. “Sekarang, ayo, makan. Kau harus mencicipi hasil karyaku.”
Di lantai kayu Jung Il Woo menggelar tikar pandan. Dihidangkannya hasil masakannya: nasi putih hangat, tumis sayur sawi hijau, bakwan goreng, dan cabe rawit. Makan siang yang istimewa.
Kim So Eun menatap Jung Il Woo. Dia seorang pria yang berteladan pada ibunya. Jadi, ia memperlakukan wanita lain seperti menjaga ibunya sendiri. Tipe pelindung sekaligus pintar memasak. Perpaduan yang unik.
“Mengapa tidak menyempurnakan lukisanmu dengan warna yang ada. Maksimalkan saja warna yang ada. Kalau ternyata warna itu tidak sesuai dengan objek aslinya, apa salahnya? Kau bukan pelukis potret. Objek yang ada hanya sekadar inspirasi, selanjutnya kemampuan kreatifmulah yang menentukan jiwa lukisanmu.”
“Tapi, aku ingin memindahkan senja yang indah itu ke kanvas.”
“Boleh saja. Tapi, jangan memasung jiwa dalam lukisanmu. Kalau hanya memindahkan objek, kamera digital mampu melakukannya dengan lebih baik. Tapi, lukisan membawa sesuatu yang berbeda, coretanmu berjiwa, merepresentasikan apa yang ada dalam dirimu.”
Kim So Eun tercenung. Dalam diam ditatapnya Jung Il Woo, nyaris tanpa kedip. Ia telah membuat banyak lukisan selama ini. Diterimanya beberapa kritik dan ulasan. Tapi, baru kali ini didengarnya analisis yang sedemikian dalam.
“Filsuf Alfred Tonele mengatakan, ‘The artist does not see things as they are, but as he is.’ Seorang seniman tidak melihat sesuatu sebagaimana adanya, melainkan sebagaimana dia kehendaki. Bukankah begitu?” tanya Jung Il Woo, serius.
Kim So Eun kehilangan kata-kata. Sosok Jung Il Woo terlalu banyak memberi kejutan.
Hari berikutnya Kim So Eun kembali ke tebing. Analisis Jung Il Woo menantangnya untuk menyelesaikan sketsa awalnya menjadi lukisan yang lebih baik, tanpa terhalang oleh koleksi warna cat airnya yang tidak lengkap. Kim So Eun ingin membebaskan dirinya menggunakan warna yang ada.
Menjelang tengah hari, matahari hampir mencapai titik kulminasinya. Panasnya bersinar dengan kekuatan penuh. Kim So Eun yang sedang asyik dengan kuas dan kanvasnya seakan terlena, tak menyadari bahwa sinar ultraviolet sedang menyerap energinya.
Sesaat kemudian serangan awal mulai menampakkan gejalanya. Pandangan Kim So Eun mulai berkunang-kunang, diikuti keringat dingin dan sesak napas, ditambah nyeri perut bawah seakan terpelintir.
Tertatih Kim So Eun mencari tempat berteduh dan bersandar di batang pohon. Perlahan diaturnya napas, meredakan sesak di dada. Diusapnya peluh di dahi, sembari menahan nyeri perutnya. Kim So Eun tahu, ia mengalami gejala awal proses pingsan. Kim So Eun memerlukan sesuatu untuk menghentikan gejala itu. Tapi, rumah Nenek Seo Woo Rim terlalu jauh. Ia tidak akan bertahan berjalan sejauh itu. Lokasi terdekat adalah pondok Jung Il Woo.
Kim So Eun menghimpun tenaga untuk berjalan ke pondok Jung Il Woo, mencari pertolongan pertama. Dengan pandangan nyaris kabur dan sisa tenaga, akhirnya Kim So Eun mampu mencapai pondok itu. Gadis itu tersungkur di beranda kayu, menimbulkan suara berdebam. Suara yang memanggil pemilik rumah.
Jung Il Woo membuka pintu dan terkejut.
“Kau pucat sekali. Ada apa?” seru Jung Il Woo, sambil meraih Kim So Eun.
“Tolong, lukisanku masih di tebing,” gumam Kim So Eun, kehabisan napas.
“Nanti kuambil. Yang penting, sekarang kau sembuh dulu,” kata Jung Il Woo, sambil memapah gadis itu masuk pondok dan membaringkannya. Dengan cepat disiapkannya teh manis.
“Minumlah, kau hampir pingsan. Apa kau tidak sarapan?”
Kim So Eun meneguk habis teh manis itu. Cairan yang melegakan dan memberikan energi baru untuknya.
“Sudah, tapi sedikit.”
Jung Il Woo menyeka peluh di dahi gadis itu. “Mungkin, kau anemia atau tekanan darahmu turun.”
Kim So Eun memejamkan mata. Nyeri perutnya makin melilit.
“Perutku sakit sekali. Ada obat gosok?”
“Tidak ada, tapi tunggu sebentar.” Jung Il Woo segera beranjak.
Beberapa saat kemudian ia kembali dengan botol kecil berisi air panas yang dibalut sapu tangan.
“Taruh ini di perutmu. Gulingkan perlahan. Pasti sakitnya akan mereda.”
Kim So Eun tampak ragu.
“Coba saja. Ibuku dulu juga melakukannya. Aku sering membantunya menggulingkan botol di perutnya.”
Kim So Eun mengangguk. “Tolong aku, segera ambil lukisanku di tebing. Kau harus cari sampai ketemu,” kata Kim So Eun.
Jung Il Woo mengangguk. “Cobalah untuk tidur sebentar supaya tensimu normal.”
Kim So Eun mengangguk.
Menjelang sore, Kim So Eun baru bangun. Begitu pulas tidurnya sehingga dia nyaris lupa berada di mana. Dia berbaring pada sebuah kasur busa tanpa dipan. Perlahan diamatinya sekeliling. Dia terbangun di sebuah ruangan sederhana yang berisi seperangkat meja gambar, gulungan kertas kalkir rancang bangun di sudut ruang, tumpukan buku arsitektur, dan CD. Di sudut meja lukisan senjanya tersandar di dinding.
Perlahan kemudian kesadarannya muncul. Detik berikutnya dirasakannya perutnya hangat. Botol berisi air itu masih menempel di perutnya. Sudah sesore ini, mana mungkin botol itu tetap panas sejak tadi siang? Pasti air panas di dalamnya sudah diperbarui. Itu berarti, Jung Il Woo sudah melihat perut dan pusarnya.
Bersambung…
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
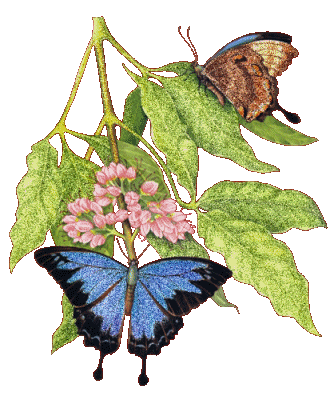
Tidak ada komentar:
Posting Komentar