Silahkan Mencari!!!
I'M COMEBACK...SIBUK CUY...KERJAAN DI KANTOR GI BANYAK BANGET...JD G BISA POSTING DEH...
AKHIRX OTAK Q PRODUKTIF LAGI BUAT FF BARU...
GOMAWOYO BWT YG DAH MAMPIR & COMMENT
HWAITING!!!
AKHIRX OTAK Q PRODUKTIF LAGI BUAT FF BARU...
GOMAWOYO BWT YG DAH MAMPIR & COMMENT
HWAITING!!!
Kamis, 28 April 2011
Luka Hati (Chapter 3)
Mata Lee Hong Ki langsung berbinar ketika tahu bahwa ia tidak akan dikeluarkan dari sekolah.
Sudah tiga hari kau tidak masuk sekolah. Ke mana saja, Lee Hong Ki?” tanyaku dengan suara pelan. Lee Hong Ki mengangkat bahu, tampangnya kusam.
“Kalau memang sakit atau ada keperluan, semestinya kau mengirim surat pemberitahuan ke sekolah. Kau tahu peraturannya, ‘kan?”
“Buat apa? Aku kan sudah dikeluarkan. Sama seperti sekolah yang dulu-dulu,” jawaban yang lugas itu membuatku tercekat.
“Siapa bilang? Kau tetap murid saya, tidak ada yang mengeluarkanmu.”
“Bohong!”
“Tidak, Saya tidak bohong. Hari Senin kau harus masuk sekolah lagi, ya? Eh, pipimu kenapa? Biru begitu,” refleks aku mengulurkan tangan hendak memeriksa. Cepat Lee Hong Ki mengelak,” Cuma kebentur pintu.”
“Nanti diobati, ya? Eh Lee Hong Ki, Saya haus. Boleh minta air putih sedikit?” aku berkelit mengalihkan pembicaraan. Tak perlu diulang dua kali, ia masuk ke dalam dan keluar membawa segelas besar air putih.
“Makan es krim lebih enak daripada minum air putih, Bu!” ujarnya tiba-tiba.
“Oh ya?”
“Ya! Warung depan jualan es krim…” kata Lee Hong Ki lagi sambil menunjuk.
“Kau mau? Ayo, kita pergi beli es krim!” aku langsung menyambar kesempatan. Siapa tahu aku bisa lebih banyak mengorek cerita dari mulutnya kalau ditemani beberapa bungkus es krim. Bak gayung bersambut, tawaran itu lantas membuat mata Lee Hong Ki bergairah.
“Boleh ambil dua, Bu?” tanyanya ketika kami sampai di depan pendingin es krim yang ada di warung, tak jauh dari rumahnya. Sambil berjalan kaki meninggalkan warung, Lee Hong Ki terus asyik menjilati makanan favoritnya.
“Apa saja yang kau lakukan selama tidak masuk sekolah, Lee Hong Ki?”
“Main, makan, nonton tv, naik sepeda.”
“Dan kau tidak memberi tahu orang tuamu kalau saya ingin bertemu?”
“Ah, bosan! Paling juga buntutnya saya keluar dari sekolah. Jadi, untuk apa saya memberitahu ayah.”
“Kau suka sekolah yang sekarang?”
“Suka.”
“Kenapa?”
“Karena ada Park Shin Hye….” Kata-kata itu terlontar keluar dan cukup jelas terdengar di telingaku. Tapi, buru-buru Lee Hong Ki meralat, ”Bukan… maksudnya eh… banyak teman baru, jadi saya suka.”
“Kalau Kau suka punya banyak teman, lalu kenapa kau pukul Park Shin Hye kemarin? Kasihan kan, pipinya diperban.”
“Salah sendiri! Siapa suruh dia pegang-pegang tangan Jang Geun Suk, lalu bisik-bisik,” jawabnya terdengar sewot. Dengan cepat ia menghabiskan sisa es krimnya.
“Memangnya kenapa?” kejarku lagi.
“Itu namanya perempuan tidak baik, pegang-pegangan dengan laki-laki. Ayah yang bilang begitu. Nenek juga,” jawabnya lugas. “Lagipula, Park Shin Hye sering mengatakan yang tidak-tidak tentang saya pada Moon Geun Young.”
“Apa katanya?”
“Dia bilang saya banci, lalu dia ketawa-ketawa sambil lihat-lihat ke belakang. Saya tahu dia sedang membicarkan saya.…”
“Lali kau marah, dan memukul Park Shin Hye? Juga melukai pipinya? Itu bukan cara marah yang baik, Lee Hong Ki. Dengan teman kita harus saling sayang, apalagi Park Shin Hye itu kan perempuan. Kalau dia jadi cacat dan bekas lukanya tidak bisa hilang, bagaimana? Kau kan bisa tanya baik-baik kenapa Park Shin Hye menertawakanmu. Sekarang akibat peristiwa ini, kau jadi tambah tidak punya teman.”
“Biarkan saja! Siapa suruh dia buang surat…” Lee Hong Ki menghentikan bicaranya, lalu memandangku sedikit salah tingkah.
“Surat apa, Lee Hong Ki?” tanyaku dengan lagak acuh tak acuh.
Lee Hong Ki menggeleng lalu katanya, ”Kita pulang saja, bu. Saya gerah, mau mandi!”
Menyadari Lee Hong Ki tidak bisa dipaksa untuk buka mulut lebih jauh, aku berusaha menyabarkan diri untuk tetap bertahan dengan pendekatan sebagai teman baginya.
“Mrs. Jang Na Ra,” kata Lee Hong Ki melangkah sambil memegang tanganku. “Betul saya tidak dikeluarkan dari sekolah?” pertanyaan yang lagi-lagi membuatku hampir sesak napas. Bagaimana mungkin aku katakan kalau nasibnya akan ditentukan dalam rapat guru minggu depan? Dan kemungkinan besar, guru-guru lebih memilih untuk mengeluarkannya. Lee Hong Ki masih memegang tanganku dan menunggu jawaban.
“Asal kau mau bertingkah laku yang baik,” sahutku mengambang sambil berharap ia puas dengan jawaban itu.
“Jadi besok Senin saya tetap bisa sekolah?” tanyanya, kali ini dengan gembira. Baru kusadari kalau binar-binar di balik kacamata tebalnya begitu hidup. “Saya tetap sekolah! Tetap sekolah!” pekiknya sambil berlari mendahuluiku. Dari kejauhan aku mengamati lonjakan gembiranya. Kesenangan yang meluap karena ia pikir sekolah tetap menerimanya. Dengan galau, aku menendang batu di depan kaki sambil memikirkan apa yang bisa aku lakukan agar kegembiraan Lee Hong Ki bisa terus dimilikinya. Kegembiraan untuk terus sekolah.
“Ayahmu sudah pulang, ya?” tanyaku ketika akhirnya kami sampai di rumah Lee Hong Ki.
“Bukan mobil Ayah. Mobil siapa itu?” Lee Hong Ki balik bertanya. Detak keras suara hak sepatu tinggi membuat kami berpaling.
“Ibu!” Lee Hong Ki melambaikan tangan dan cepat menghampiri wanita yang sedang menutup pagar di belakangnya. Wajahnya lumayan tebal dengan make up, gaya busananya modern, dengan dua jari tangan menjepit rokok yang mengepul.
“Main terus! Tidak naik kelas lagi baru tahu rasa!” semprotnya tanpa mengacuhkan tangan Lee Hong Ki yang terbuka minta dipeluk.
“Mobil baru ya, Bu? Mau ke mana, Bu? Aku kan belum …!” teriak Lee Hong Ki penuh protes melihat Ibunya membuka pintu mobil. Dia mengejar dan menahan pintu mobil, tapi tangan Lee Hong Ki segera ditepisnya dengan kasar. “Apa-apaan kau ini? Minggir!” Bentakannya membuat Lee Hong Ki mundur menjauhi mobil.
“Hei, bilang pada Ayahmu, mana uang bulanannya? Janji jam 5 sore, malah dia belum pulang. Sialan!”
Lee Hong Ki cuma terlongo mengikuti deru mobil yang berputar meninggalkan rumahnya. Gerakan tangannya yang dalam posisi siap melambai perlahan turun dengan lemas. Aku hampir tidak percaya kalau adegan barusan adalah adegan antara ibu dan anak. Lebih mirip adegan nyonya besar dengan kacungnya.
“Lee Hong Ki!” panggilku. “Itu Ibumu?”
Dia memandangku dari balik kacamata tebalnya dan mengangkat bahu, lalu berbalik masuk dan menutup pintu. Dari balik kaca ia mengawasiku melangkah pulang. Aku melambaikan tangan pamit pulang dan melaju membawa kegalauan besar dalam hati. Surat panggilan yang diberikan Mr. Bae Yong Jun tadi masih tersimpan di dalam tasku.
Aku menguap panjang sambil melemaskan otot-otot pinggang. Uah, masih ada enam karangan lagi yang harus aku baca. Di kelas aku paling suka memberikan ulangan dalam bentuk esai dan pelajaran favoritku adalah pelajaran mengarang. Karena dari hasil tulisan yang mereka tulis itulah aku bisa membaca jalan pikiran murid-murid. Sekaligus melatih mereka menuangkan ide dan kreasi dalam bentuk kalimat. Hitung-hitung memberikan bekal kalau kelak mereka menginjak kuliah nanti, harus membuat laporan praktikum dan menyusun skripsi. Menurutku bahaya kalau mereka terus terkondisi dengan kemudahan memilih jawaban pilihan berganda, yang mendorong kegiatan mencontek tumbuh dengan subur.
Seperti hari ini, aku menyuruh murid-murid membuat karangan tentang sosok ibu masing-masing. Ada yang menulis, ibunya galak seperti tentara tapi ia sangat sayang karena ibunya jago memasak mi ayam kesukaannya. Yang lain bercerita, ibunya selalu pergi ke kantor pagi-pagi dan pulang malam hari, padahal ia ingin berbagi cerita tentang aktifitasnya hari itu sebelum tidur.
Aku melihat sisa karangan yang tergeletak sembari menimbang untuk menunda memeriksanya, besok pagi saja. Tapi sehelai kertas bertuliskan nama Lee Hong Ki menarik perhatianku. Karangannya teramat singkat, kalimat-kalimatnya pendek dan sederhana, dengan alur cerita yang tidak terarah.
Aku punya Ibu. Ibu yang melahirkan aku. Ibuku cantik. Bajunya bagus-bagus. Ibu sering pergi. Aku ingin pergi ke Taman Hiburan dengan Ibu. Tapi Ibu pergi terus. Ibu sayang padaku.
Rasa kantukku berangsur hilang, berganti dengan keprihatinan. Sedari pertama ketika melihat ayahnya mengantar Lee Hong Ki ke sekolah di hari pertama, aku tergelitik dengan sikap anehnya. Dan ketika berkunjung ke rumah Lee Hong Ki serta melihat seperti apa keluarganya, aku langsung mengerti mengapa Lee Hong Ki begitu berbeda dengan anak-anak lain. Bukan hanya hatinya yang sakit, tapi juga jiwanya. Rasa tertolak karena kehadirannya tidak dikehendaki oleh sang ibu berbaur dengan pendaman kerinduan untuk merasakan kehangatan kasihnya, bercampur dengan kemuakan karena sang ibu mengkhianati keluarganya. Apalagi dia sedang menginjak puber, yang sering krisis karena mencari jati diri. Masih segar di mataku, guratan kecewa yang tidak bisa disembunyikan Lee Hong Ki ketika ibunya sama sekali tidak menyapanya dengan manis sore itu, apalagi berinisiatif memeluknya. Bahkan, untuk sebuah lambaian tangan yang sederhana.
Aku tidak bisa membayangkan seperti apa pedihnya, tidak dicintai oleh ibu sendiri sedari bayi. Ditambah lagi harus menyaksikan ulah tak terpuji dari ibu yang sangat dipujanya. Aku juga tak bisa membayangkan seperti apa rasanya menjadi orang yang terbelakang mental, dengan tubuh sebesar remaja tapi berpikiran seperti anak-anak. Dikeluarkan dari sekolah, dijauhi teman, dimarahi guru, tidak memiliki siapa pun untuk diajak bicara, dan selalu dianggap sebagai orang aneh yang membawa masalah. Tidak ada yang mau mengerti, seorang pun tidak. Ya Tuhan, seperti apa rasanya? Malam itu sebelum tidur, aku menyelipkan nama Lee Hong Ki dalam permintaan doaku. Tanpa sadar aku ikut menangis.
"Jadi begitu ceritanya?” Wang Ji Hye mengangsurkan sepiring makaroni skotel di depan hidungku. Aku mengiyakan sambil mengunyah. Sepulang dari took buku aku menyempatkan mampir ke tempat kos Wang Ji Hye. Usianya 5 tahun di atasku, tapi tidak pernah bersikap sok senior dan sok tahu seperti kakak kelasku yang lain. Kami dulu sudah saling mengenal ketika kuliah di perguruan tinggi yang sama dan sekarang kebetulan mengajar di sekolah yang sama pula. Tapi sesuai dengan latar belakang pendidikannya di fakultas psikologi, ia ditempatkan di bagian BP dan konseling.
“Ternyata masalahnya kompleks. Maksudku…kita harus melihat kenakalan Lee Hong Ki itu karena jiwanya yang terguncang. Jadi kita tidak bisa menghakiminya begitu saja, mengeluarkan dari sekolah lalu urusannya beres. Bagaimana menurutmu?”
“Ya, aku setuju.”
“Mendengar cerita tadi, bagaimana kira-kira analisismu?” aku berguling ke sudut tempat tidur dan menemukan bantal berbentuk gajah yang cukup empuk untuk kutiduri.
“Lee Hong Ki mengalami trauma, itu jelas. Ia tidak menerima cukup cinta dari orang-orang yang semestinya memberikan itu. Sejak kelahirannya saja, ia sudah ditolak oleh sang ibu. Mengingat kesenangannya berdandan dan kepeduliannya pada tubuh, mungkin ia menganggap hamil dan melahirkan adalah kerusakan yang bisa mengancam keindahan tubuhnya. Dan ancaman itu berwujud seorang anak, yang langsung ia benci. Luka batin yang sudah ditaburkan sejak bayi terus menambah parah keadaan, ditambah lagi perbuatan ibunya yang gemar gonta-ganti pasangan. Kenyataan itu agaknya terlalu berat bagi Lee Hong Ki, sehingga jiwanya labil dan kita bisa lihat dari sikapnya sehari-hari, ‘kan? Kadang mengamuk, kadang alim, kadang agresif.”
“Kenapa bisa begitu?”
Bersambung…
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
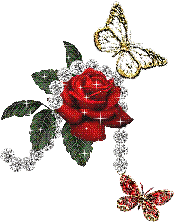
Tidak ada komentar:
Posting Komentar