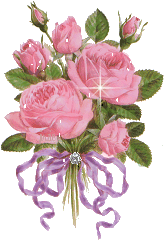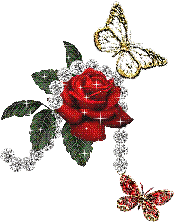Sekadar iseng mau tahu, kulongok isinya. Kertas surat rupanya sudah disobek-sobek menjadi beberapa potong, dan karena iseng juga aku menyusunnya lagi seperti menyusun puzzle. Walaupun surat itu tak mencantumkan nama penulis, tapi aku hafal tulisan tangannya. Surat dari Lee Hong Ki untuk Park Shin Hye.
Ketika melihat sekretaris Mr. Bae Yong Jun melintas, aku langsung mengejarnya,”Mrs. Kim Ha Neul! Mr. Bae Yong Jun masih sibuk tidak?”
“Sudah pulang dari pukul 5 tadi. Memangnya ada janji bertemu?”
“Tidak, hanya saja urusan yang tadi belum beres.”
“Ehm, masalah anak itu ya, siapa namanya?”
“Lee Hong Ki,” jawabku.
“Sudahlah Mrs. Jang Na Ra, besok lagi saja. Sekarang lebih baik kau pulang, istirahat supaya pikiran jadi jernih lagi. Mau pulang sama-sama? Kebetulan saya bawa mobil,” ajak Mrs. Kim Ha Neul yang langsung kusetujui.
Betul juga, lebih baik pulang. Mandi air hangat sambil berendam. Berpikir dengan kepala suntuk begini tidak ada gunanya sama sekali. Besok apa pun yang terjadi, terjadilah.
Mandi air hangat memang manjur untuk menyegarkan pikiran. Ditemani segelas susu coklat, aku menghabiskan waktu di ranjang sambil memejamkan mata. Pikiranku menerawang. Apakah Lee Hong Ki itu menyebalkan? Jawabnya, ya. Apakah dia selalu membuat kekacauan? Ya. Setiap hari? Ehm…tidak juga. Ada hari-hari tertentu anak itu berlaku seperti pertapa, tidak suka diganggu. Apakah dia dibenci semua orang? Ya, termasuk aku. Gara-gara anak itu, karirku terancam. Apakah dia tidak memiliki sesuatu yang bisa membuat orang menyayanginya? Ehm, rasanya tidak ada. Semua dalam diri anak itu memang menyebalkan. Pantas saja, sering tidak naik kelas dan dikeluarkan dari sekolah. Mana ada orang yang tahan dekat-dekat dengannya? Aku menguap lalu memutuskan untuk mencoba tidur walaupun mataku masih betah terbuka.
Ketika subuh aku terbangun, dan mengingat-ingat apa yang kualami semalam. Mimpi atau bukan, ya? Aku seolah berada di ruang persidangan dengan Lee Hong Ki sebagai tertuduh utama. Mr. Bae Yong Jun memakai jubah hakim dan memegang palu. Sementara aku berdiri kebingungan, harus duduk di mana. Di ruangan itu ada dua meja yang kosong. Yang satu bertuliskan PEMBELA, dan yang satu bertuliskan SAKSI. Anehnya, di meja jaksa berkumpul banyak sekali orang.
Persidangan dimulai dengan cepat. Banyak orang berebut menudingkan jari ke arah tertuduh supaya dipenjara saja. Tertuduh hanya diam, tak bisa membela diri. Sementara para jaksa membacakan tuntutannya, ia hanya menangis. Airmatanya makin lama makin deras, membasahi lantai dan akhirnya memenuhi ruang sidang. Kasihan sekali. Kulihat di sekeliling, tak seorang pun yang membawa saputangan untuk diberikan pada tertuduh agar tak lagi menangis.
Tiba-tiba entah dari mana datangnya, tangan kananku menggenggam sehelai saputangan merah. Dan entah bagaimana juga, tahu-tahu aku menghampiri tertuduh, mengelap wajahnya yang basah. Ajaib, airmatanya berhenti. Lantai tidak lagi basah, dan ruangan jadi kering. Ketika palu hakim akan diketuk, suara jam weker mengagetkanku. Saat itulah aku terbangun.
Sambil mandi dan menyiapkan bahan pelajaran untuk hari ini, aku terus sibuk mengartikan mimpi barusan. Kebetulankah? Atau bermakna khusus? Mendadak aku teringat nasib pekerjaanku yang di ujung tanduk, dan hatiku pun menciut.
Hari ini dua muridku tidak masuk kelas, Park Shin Hye dan Lee Hong Ki. Perasaan bersalah yang makin besar membuatku tidak tenang mengajar. Ditambah lagi dengan kemungkinan aku mendapat sanksi keras karena peristiwa kemarin. Kalau hanya teguran atau peringatan, itu masih lebih baik. Tapi kalau aku sampai dipecat?
Setelah anak-anak kelas pagi pulang, aku langsung menghambur ke ruangan Kepala Sekolah dan menemui sekretaris Mr. Bae Yong Jun. “Mrs. Kim Ha Neul, apa Mr. Bae Yong Jun ada?”
“Sedang rapat di kantor pusat,” jawab yang ditanya sambil terus mengetik di komputer.
“Pulangnya jam berapa?”
“Ehm..sampai sore rapatnya. Mungkin tidak balik ke sekolah.”
“Oh, terimakasih ya.”
Esok harinya jawaban yang sama kuterima lagi.
“Rapatnya berapa hari?”
“Sampai Jumat ini.”
“Mr. Bae Yong Jun tidak menitipkan apa-apa untuk saya? Surat misalnya?”
“Surat? Tidak, kalau memang penting sekali, telepon saja ke ponselnya.”
“Apa kau yakin, tidak ada surat sama sekali yang harus disampaikan kepada saya?”
“Tidak ada, Sayang….”
Tanpa sadar aku menghembuskan napas lega. Tapi kelegaan itu umurnya tak lama. Hari Sabtu, tiga hari setelah kejadian itu, aku dipanggil menghadap Kepala Sekolah. Dalam ruangan aku melihat Mr. Bae Yong Jun sedang menimang-nimang sepucuk surat. Sekuat tenaga aku menahan perasaan.
Jadi, memang ini akhirnya…. Susah payah aku melamar kerja di sini, bukan kondite baik yang aku dapatkan malah surat pemecatan karena sakit perut yang konyol. Tak bisa kubayangkan kata-kata yang tertulis di dalamnya.
“Menyambung pembicaraan kita tempo hari, tindakan apa yang sudah Anda ambil sehubungan dengan kejadian kemarin?”
“Ehm…saya sudah menghubungi bagian konseling dan guru BP untuk berdiskusi tentang masalah ini, tapi belum tuntas. Saya juga sudah memerintahkan orangtua Lee Hong Ki untuk datang, tapi sampai hari ini mereka tidak menemui saya. Lee Hong Ki sendiri tidak masuk sekolah sejak peristiwa itu. Saya sudah mencoba menghubungi lewat telepon rumahnya, tapi tidak diangkat.”
“Kalau begitu, langsung saja Anda berikan surat panggilan terakhir ini untuk orangtua Lee Hong Ki. Anda antarkan sendiri saja ke rumahnya,” Mr. Bae Yong Jun mengangsurkan surat yang sedari tadi ditimang-timangnya.
“Hah? Jadi…ini….ini surat untuk Lee Hong Ki?” ekspresi kekagetanku tak bisa ditutupi.
“Memang Anda pikir surat apa?” Mr. Bae Yong Jun balik bertanya. Syukur Tuhan, syukur! Aku pikir surat yang diberikannya adalah surat ‘kematianku’.
“Apakah dengan surat ini juga berarti Lee Hong Ki sudah dikeluarkan?”
“Rapat guru Senin depan akan memutuskan hal itu. Tapi Anda tidak perlu memusingkannya, Anda sendiri sudah sangat jengkel dengan kelakuannya bukan?”
Ya, aku memang jengkel dengan kelakuan Lee Hong Ki. Amat sangat jengkel. Kadang kalau emosiku sudah terlalu mendidih, ingin rasanya melumat kepala anak itu dan melihat apa saja isi otaknya. Tapi untuk mengeluarkannya dari sekolah, rasanya aku tidak tega. Kasihan, mungkin itu alasan yang lebih tepat.
Aku merapikan rambut sebelum memencet bel pintu. Dari dalam rumah yang tidak terlalu besar itu terdengar langkah kaki yang diseret. Seraut wajah wanita tua menyembul sedikit dari balik kaca.
”Cari siapa?” tanyanya judes.
“Saya Jang Na Ra, guru sekolah Lee Hong Ki. Saya ingin bertemu orangtuanya karena masalah yang Lee Hong Ki alami di sekolah. Saya sudah meminta mereka datang ke sekolah kemarin, tapi orangtua Lee Hong Ki tidak datang. Maaf, Nyonya ini…”
“Neneknya,” jawab wanita itu tanpa berniat membuka pintu lebih lebar, apalagi mempersilakan masuk.
“Maaf, kita bisa bicara di dalam? Saya rasa Lee Hong Ki mempunyai masalah yang cukup membutuhkan bantuan,” aku memasang senyum sedikit memohon, berlagak tidak tahu wajahnya sudah seasam cuka. Setelah yakin aku tidak bertampang mirip penjual barang keliling, wanita tua itu mau juga melebarkan pintu.
Begitu masuk, suasana sumpek langsung terasa. Rumah itu penuh sesak dengan barang yang ditumpuk begitu saja. Aku mencari-cari potret keluarga di tembok, tapi tak kutemukan.
“Ada perlu apa?” tanya Ny. Kim Sun Ah - nenek Lee Hong Ki setelah kami duduk berhadapan. Rupanya dia penganut paham tembak langsung.
“Bisa saya bertemu dengan orangtua Lee Hong Ki sekarang?”
“Ayahnya sedang pergi. Kerja.”
“Oh, ibuanya saja kalau begitu.”
“Dia tidak di sini!” Ny. Kim Sun Ah mendengus dengan mulut mencibir. Aku mengerutkan kening menunggu penjelasan lebih lanjut.
“Di dapur banyak pekerjaan, jadi cepat saja kau katakan ada perlu apa datang ke sini. Kalau hanya ingin bertemu orangtua Lee Hong Ki, bukankah sudah saya katakan tidak ada!” cetusnya tanpa tedeng aling-aling.
Aku meremas ujung amplop surat yang terasa menonjol di tas kecilku, dan siap melaporkan tentang berbagai kenakalan yang dilakukan cucunya di sekolah. Sekaligus membawa hadiah surat panggilan yang tidak main-main.
“Saya…begini, saya ingin berkenalan lebih dekat dengan keluarga Lee Hong Ki. Dia murid baru di kelas saya, jadi saya pikir saya ingin mengenalnya lebih dekat. Saya juga sering mengunjungi murid-murid yang lain, kebetulan hari ini giliran Lee Hong Ki. Ibu Lee Hong Ki sedang ke mana?” aku sedikit berputar-putar mencari celah.
“Buat apa aku tahu ke mana perginya wanita itu! Dia sudah tidak tinggal di sini lagi!” jawabnya ketus.
“Wah, bagaimana ya? Saya harus menyampaikan surat panggilan dari sekolah untuk orangtua Lee Hong Ki. Mungkin Nyonya tahu di mana saya bisa menghubunginya? Kenapa Lee Hong Ki tidak bilang ya kalau punya rumah baru,” kataku dengan nada bingung.
“Kau ini bagaimana? Aku bilang tidak tahu ya tidak tahu! Sudah lama dia tidak tinggal di sini, kabur dengan laki-laki lain. Caci maki pun meluncur dari mulut wanita tua itu. Kini aku baru tahu darimana Lee Hong Ki belajar makian seperti itu. Belum sempat aku bertanya lagi, Ny. Kim Sun Ah menyambung lagi.
“Salah Song Seung Hun juga, pilih istri model begitu! Dari dulu aku sudah bilang, cari penyakit kalau dapat istri yang tukang dandan seperti dia. Aku sudah bosan memperingatkan bakal terjadi apa-apa, nah kenyataannya begini kan? Perempuan itu minggat setelah tertangkap basah berselingkuh di rumah ini,” wajah masam di depanku berubah bersemangat waktu menceritakan keburukan menantunya. Gayanya bercerita seperti tukang gosip yang membawa berita hangat.
“Jadi sekarang mereka bercerai?”
“Tidak tahulah apa namanya. Bodohnya Song Seung Hun terlalu cinta pada Park Si Yeon, sudah dikhianati tetap saja tidak mau pisah! Mungkin Song Seung Hun sudah diguna-guna…Sebulan sekali wanita brengsek itu datang kemari. Bukan untuk bertemu anak-anaknya, tapi hanya mengambil jatah uang dari Song Seung Hun.”
“Lalu bagaimana dengan anak-anak? Pasti mereka kehilangan sekali….”
“Ah, kehilangan bagaimana? Kau tahu, Lee Hong Ki dan Minho - adiknya sejak lahir tidak pernah diurus. Anak menangis minta susu, dia malah pasang musik kencang-kencang di kuping. Ganti popok saja dia tidak mau. Perempuan itu hanya pintar mengurus badan, rambut, bedak, dan kuku. Cuma itu saja bisanya! Oh, ada lagi kebisaannya, main bentak dan main pukul. Kalau ditegur pelan-pelan, segala macam benda pasti dibanting sampai berantakan. Adat perempuan itu memang luar biasa jeleknya! Kasihan Lee Hong Ki, padahal ia sayang sekali pada ibunya itu. Pernah sekali waktu ia menabung untuk membelikan cat kuku untuk ibunya, tapi boro-boro dipakai, dilihat saja tidak,” lagi-lagi Ny. Kim Sun Ah mencibir. Kelihatannya ia ingin semua orang tahu keburukan apa saja yang dibuat menantunya.
“Ah, tadi Kau bilang kalau Lee Hong Ki punya masalah. Kenapa lagi dia di sekolah? Berkelahi lagi?”
“Begitulah. Seorang teman perempuan dipukulnya tapi Lee Hong Ki tidak mau cerita kenapa ia berbuat begitu.”
“Maklumi saja, siapa namamu?”
“Jang Na Ra.”
“Ya, Maklumi saja Mrs. Jang Na Ra. Namanya saja anak-anak, wajar kan kalau nakal sedikit, berkelahi sedikit? Lee Hong Ki memang kurang mendapat perhatian, tapi bagaimana lagi? Ayahnya setiap hari harus kerja, ibunya minggat, dan aku harus mengurus toko di rumahku sendiri. Asalkan mereka bisa sekolah di tempat yang bagus, makan enak dan punya mainan banyak, rasanya itu sudah cukup bagus,” Ny. Kim Sun Ah menatap mataku dalam-dalam, seolah bilang bahwa aku tak berhak ikut campur dalam urusan keluarganya.
“Ny. Kim Sun Ah tahu kenapa Lee Hong Ki sampai dikeluarkan dari beberapa sekolah?”
“Hah, memang sekolahnya saja yang brengsek! Mereka bilang Lee Hong Ki terlalu bodoh, terlalu nakal. Mereka bilang, seharusnya Lee Hong Ki masuk ke SLB. Penghinaan itu namanya! Mereka tidak lihat kalau di rumah Lee Hong Ki itu manis seperti bayi! Sekolah kalian tidak seperti itu kan?” tanyanya dengan nada sedikit mengancam.
“Oh tidak….Ehm, maaf Ny. Kim Sun Ah, tapi kalau saya boleh tahu… apakah Lee Hong Ki tahu tentang perselingkuhan ibunya?”
“Oh tentu! Aku yang menceritakannya. Malah Lee Hong Ki sendiri pernah menangkap basah perbuatan Ibunya, lima tahun yang lalu. Waktu itu kami pergi ke Incheon, ada famili yang menikah. Dan Song Seung Hun mempercepat kepulangan sehari karena kuatir dengan Park Si Yeon yang sedang mengandung tua, Minho - adik Lee Hong Ki. Begitu sampai di rumah…” Ny. Kim Sun Ah berhenti sebentar lalu meneruskan dengan kedua tangan saling meremas, ” Lee Hong Ki yang pertama turun dari mobil. Dia lari masuk ke dalam sambil membawa dua kotak kue oleh-oleh untuk Ibunya. Tapi begitu Lee Hong Ki membuka pintu kamar, ia melihat adegan yang semestinya tidak boleh ia lihat. Laki-laki itu ada di sana, bersama dengan Ibunya. Ia tidak menjerit atau berteriak, tapi ia hanya memandang mereka lalu keluar sambil meremas kue di tangannya, satu per satu hingga remuk semuanya. Kue itu berceceran sampai ke ruang ini.
Lee Hong Ki juga melihat ketika Ayahnya menghajar laki-laki itu sampai babak belur, tapi ia hanya diam sambil duduk bersandar di tembok. Waktu itu suasananya kacau sekali, tidak ada yang ingat kalau anak itu tidak boleh menonton kesadisan yang tidak patut. Setelah dihajar, mereka lantas kabur dan hidup serumah sampai hari ini. Sudah aku bilang supaya menceraikan perempuan itu, tapi Song Seung Hun tetap tidak mau. Kasihan anak-anak, katanya. Kasihan apa? Setiap hari dia ada di rumah ini juga tidak pernah menyentuh anak-anaknya.”
“Apakah Lee Hong Ki menunjukkan perubahan sikap setelah kejadian itu, Ny. Kim Sun Ah?”
Dengan pasti Ny. Kim Sun Ah menggeleng. “Tidak. Hari-hari berikutnya sampai sekarang ini, ia tetap bersikap biasa. Ya kalau nakal-nakal sedikit wajarlah, namanya juga anak-anak. Sebenarnya dia tidak bodoh, tapi malas belajarnya itu yang minta ampun! Aku juga heran kenapa sampai tiga kali tidak naik kelas, dipanggilkan guru les sudah, tapi ya tetap saja begitu. Jangan-jangan memang gurunya yang tidak becus mengajar… Bukan begitu, Mrs. Jang Na Ra?” cemoohnya.
Aku berusaha mencerna kembali apa yang barusan aku dengar. Mengejutkan sekaligus membingungkan. Apakah latar belakang keluarga yang kacau menyebabkan Lee Hong Ki berperilaku aneh seperti itu?
Suara pintu terbuka membuat kami berpaling. Lee Hong Ki berdiri sambil mengucek mata, baru bangun tidur tampaknya. “Hei Lee Hong Ki, kemari! Ini ada Gurumu, katanya mau menjengukmu. Ayo kemari!” Ny. Kim Sun Ah melambaikan tangan menyuruh Lee Hong Ki mendekat. Aku mendengar ia dipanggil berkali-kali dengan ucapan kasar, dan sang Nenek hilang sabar. Dengan bengis ia menyeret Lee Hong Ki ke luar, memaksanya bertemu denganku.
“Itu Gurumu, mau bertemu denganmu! Duduk!” bentaknya lalu menghilang ke dalam. Lee Hong Ki duduk dengan pantat hanya setengah menempel di sofa hijau yang sudah pudar warnanya. Matanya menatap curiga.
Bersambung…